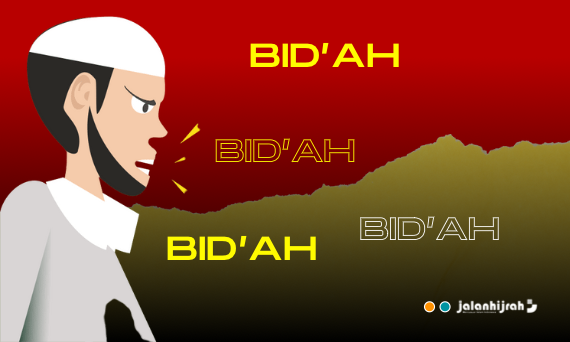Jalanhijrah.com- Momentum Ramadan menjadi salah satu momen yang memberikan ruang sangat luas untuk belajar. Bayangkan saja, selama satu bulan, umat muslim memiliki waktu yang sangat panjang untuk ke masjid, mengikuti sholat tarawih, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain.
Di Yogyakarta misalnya, hampir setiap masjid dalam pelaksanaan tarawih, disertai dengan ceramah atau yang bisa kita sebut kultum, dengan pelbagai bahasan menarik tentang keagamaan untuk menambah wawasan kita.
Di masjid kampus UGM Yoyakarta, ceramah tersebut disampaikan oleh banyak tokoh-tokoh nasional, pembahasannya pun sangat akademik untuk menambah wawasan kebangsaan. Ramadan seperti bulan ilmu, sebab semuanya memiliki nuansa pengetahuan yang tidak terbatas pada sudut-sudut masjid.
Kegiatan seperti itu rasanya sangat naif jika disebut bid’ah oleh sebagian kelompok. Padahal, ceramah tersebut adalah ruang untuk belajar yang sangat luas bagi mahasiswa, serta kelompok masyarakat lain untuk bersama-sama mengejar berkah Ramadan sebagai bulan yang mulia.
Tingkatan seseorang dalam belajar
Saya ingat betul ketika pertama kali belajar agama, misalnya tentang kewajiban menutup aurat. Pengetahuan baru tersebut membuat saya harus seperti ideal yang di abstraksikan oleh otak. Dengan begitu, ketika saya sudah menutup aurat dari ujung rambut saya ujung kaki, sikap merasa paling suci, dan menganggap orang lain yang tidak sama dengan saya adalah berdosa merupakan hal utama dalam pikiran.
Lambat laun, pengetahuan tersebut di tambah dengan pengalaman, lingkungan, bertemu dengan banyak orang yang berbeda, belajar dengan orang yang memiliki pemikiran yang berbeda dan pemahaman agama yang berbeda. Dari situlah, standart ideal yang sebelumnya sempit, semakin berubah. Artinya, pemahaman tersebut tidak merubah ketentuan agama. Melainkan merubah pemahaman saya atas ajaran agama.
Barangkali kisah di atas juga bisa dijadikan cerminan kepada kita tentang, orang-orang di sekitar yang masih berkutat dengan standart kebenarannya sendiri, memaksa orang lain untuk sama dengan pemahamannya, membid’ahkan orang lain bahkan mengkafirkan hanya karena tidak seperti pemahaman yang dimiliki.
Kita perlu ingat bahwa, ketiadaan sikap menghargai itulah yang menjadi problem kita pada hari ini. Merasa paling Islam, sedangkan yang lain tidak Islam. Merasa bahwa praktik keberagamaan yang lain adalah salah, sedangkan kelompoknya yang benar. Maka dari itu, Musdah Mulia menjelaskan bahwa, dengan fenomena ini, pentingnya dialog agama agar terus dilakukan untuk menambah pemahaman agama yang sangat kompleks agar bisa menjadi pluralis.
Mencari guru ideal dalam konteks beragama dan berbangsa
Setiap orang memiliki standart ideal masing-masing. Akan tetapi, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, wajib hukumnya kita belajar agama pada orang yang tidak bertentangan dengan negara, tidak mempermasalahkan Pancasila sebagai dasar negara, serta tidak memperdebatkan celah pemerintah untuk mengubah dasar negara.
Tidak hanya itu, guru agama yang kita jadikan panutan, harus bisa melihat keanekaragaman pemahaman agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa, pemahaman Islam yang berbeda-beda dari masing-masing kelompok, seharusnya menjadi kekayaan bagi wawasaan kita. Seorang guru harusnya menjelaskan perbedaan itu, bukannya mencaci maki bahkan mengumpat karena perbedaan.
Dengan demikian, Prof. Quraish Shihab, dalam sebuah video youtube bersama Najwa Shihab, menjelaskan bahwa, guru dalam belajar agama haruslah memiliki paham wasathiyyah (moderat). Hal ini mengapa penting? Karena Islam terdiri dari banyak pendapat dan aliran. Orang moderat merupakan orang yang memiliki keluasan pengetahuan untuk menerima perbedaan serta tidak menghakimi praktik beragama orang lain.
Dalam artian, dari guru agama yang moderat, kita tidak akan mendengarkan caci maki, kekesalan karena perbedaan pendapat dan praktik agama yang berbeda. Karena dirinya memahami bahwa sejak zaman Rosulullah, perbedaan pemahaman sudah biasa terjadi di kalangan sahabat. Apalagi pada era saat ini, Al-Quran dan hadis yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang.
Maka bisa disimpulkan bahwa, seyogyanya guru agama yang bisa mentolerir perbedaan penting untuk dijadikan guru. Sebab ia memiliki pengetahuan yang amat luas tentang banyaknya praktik keberagamaan. Tinggalkan guru yang mencaci maki praktik keberagamaan orang lain, dan menganggap bahwa hanya praktik agama dirinyalah yang benar! Gus Dur pernah berkata bahwa, “ Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi toleransinya.” Wallahu a’lam
*Penulis: Muallifah Mahasiswi Magister Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Bisa disapa melalui instagram @muallifah_ifa